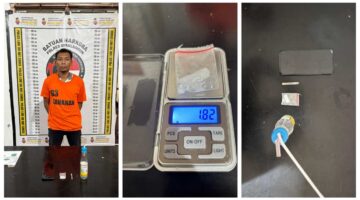EDITORIAL KHUSUS
LEUSER NEWS | Di dataran tinggi Pantan Cuaca, Gayo Lues, ribuan petani hidup dari satu hal yang mereka yakini sebagai warisan paling berharga: kopi Arabika Gayo. Bukan emas. Bukan logam mulia. Tapi kopi. Sebab di sana, secangkir kopi bukan hanya soal rasa, melainkan harga diri.
Maka ketika alat berat milik PT Gayo Mineral Resources (GMR) mulai mengoyak perut bumi, masyarakat tahu: ini bukan sekadar eksplorasi tambang, ini ancaman langsung terhadap kehidupan mereka. Ketika sungai berubah warna, ketika lumpur mengalir ke sawah, ketika binatang mulai hilang dan air berbau logam, masyarakat sadar: emas itu terlalu mahal dibayar dengan kehancuran ekosistem yang telah mereka rawat turun-temurun.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka tidak tinggal diam. Petani di Pantan Cuaca menulis surat kepada Presiden. Mereka bukan menuntut uang, bukan memohon bantuan, tapi memohon satu hal: cabut izin tambang, selamatkan tanah kami. Karena bagi mereka, kopi bukan sekadar komoditas, melainkan identitas. Dan tambang adalah ancaman langsung yang dapat menghapus identitas itu dalam hitungan tahun.
Masalahnya, perjuangan mereka tak berjalan seimbang. Di balik aktivitas tambang yang mencurigakan itu, masyarakat mencium bau busuk kekuasaan. Ada dugaan bahwa oknum di dalam DPRK ikut bermain mata—berpaling dari amanat rakyat demi mengamankan kepentingan pemodal. Bukannya mengawal suara petani, mereka malah sibuk melindungi proyek perusak bumi. Pertanyaan yang kini menggantung di langit Gayo Lues: apakah wakil rakyat masih berpihak pada rakyat, atau sudah berpindah pada logam mulia?
Yang menyedihkan, proyek ini bahkan tak memiliki pijakan hukum yang kokoh. Legalitas lokasi tambang diduga dimanipulasi. Peta kerja yang dipakai justru berasal dari Maluku Utara, padahal alat berat menggali hutan lindung di Pantan Cuaca. Ini bukan kelalaian. Ini dugaan manipulasi. Tambang emas di tengah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)—yang diakui dunia sebagai warisan penting planet ini—berjalan tanpa konsultasi publik, tanpa dokumen AMDAL yang jelas, dan tanpa izin pemanfaatan kawasan hutan (IPPKH). Ini pelanggaran demi pelanggaran yang dibungkus legalitas semu.
Di tengah semua itu, para petani hanya punya satu senjata: suara. Dan mereka kini sedang menggunakannya untuk berteriak, meski dari pegunungan yang sunyi. Mereka menolak jadi korban dari permainan elite dan investor. Mereka menolak jadi angka dalam grafik pertumbuhan ekonomi yang palsu. Sebab yang mereka perjuangkan adalah air bersih, tanah subur, dan masa depan generasi mereka.
Petani Gayo tak butuh tambang emas. Mereka hanya ingin sawah tetap dialiri air jernih. Mereka hanya ingin kopi Gayo tetap harum di pasar dunia. Mereka hanya ingin anak cucu mereka bisa tumbuh dari tanah yang sehat, bukan tanah yang diracuni limbah logam berat. Mereka ingin negara hadir, bukan sebagai makelar investasi, tapi sebagai pelindung kehidupan.
Hari ini, suara petani Gayo adalah ujian bagi negara: apakah Republik ini masih berpihak pada rakyat kecil yang menjaga bumi, atau telah sepenuhnya diserahkan ke tangan-tangan rakus yang menambang masa depan?
Gayo tak butuh emas. Karena yang berkilau di sana bukan logam, tapi dedikasi, kerja keras, dan cinta terhadap tanah. Maka biarlah tambang itu pergi. Biarlah tanah itu tetap ditanami kopi. Sebab hanya kopi Arabika yang hidup di hati masyarakat Gayo—bukan emas yang meracuni sungai dan nurani. (*)